Ciyeeh … si Octa mau nulis agak serius hari ini.
Hari ini anak-anak sekolah hari pertama, jadi saya punya waktu di depan PC lebih lama dan lebih tenang. Selama liburan kemarin, si Tole pakai PC buat main games, jadi musti gantian sama doi. Maksud hati, sih, pagi-pagi udah mau duduk di depan PC dan mulai ngerjain ini-itu, gitu, tapi yang ada saya malah baca-baca buku, lihat paper, dan baca tulisan ini:


Trus, jadinya saya ngopi di depan PC, baca … mikir … dan kepala tahu-tahunya penuh. Hadeh. 😣
Trus saya pindah ke paper yang semalem di-share sama si Tuan buat referensi saya, tapi kok … paper ini, menarik banget tapi enggak bikin perhatian saya pindah dari pikiran saya sebelumnya.
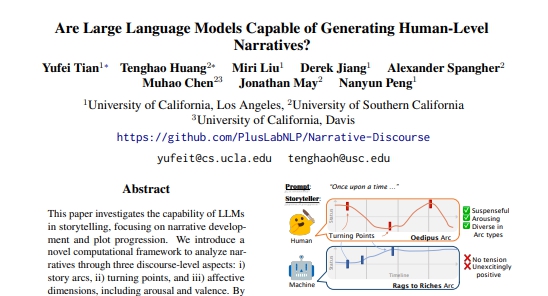
Jadi, saya memutuskan buat nulisin apa yang ngeganggu dan menuh-menuhin otak saya dulu sebelum saya balik ngerjain apa yang emang musti saya kerjain hari ini. 😣
* * *
Kenapa Kita Enggak Nonton Bareng Lagi
Jaman saya remaja dan muda dulu (ciyeh), kalo ada satu film, sinetron, atau acara yang tayang di televisi, semua orang bakalan tahu. Bukan karena promosi besar-besaran, tapi karena semua orang nonton hal yang sama pada waktu yang sama. Lagu diputar di mana-mana, sinetron jadi topik obrolan, dan bahkan yang enggak pernah nonton pun tetap tahu karena diceritain orang. Nonton bukan sekadar aktivitas hiburan, tapi bagian dari hidup sosial. Kita tertawa, kaget, dan sedih bersama. Bahkan diam pun bisa dirasakan bareng-bareng.
Semua murid bakalan bahas tontonan di televisi keesokan harinya di sekolah saya. Yang ngebedain cuma; kamu masuk sekolahnya pagi atau siang? Kalo kamu masuk pagi, kemungkinan kamu nontonnya acara pagi, kalo siang, kamu nontonnya acara sore. Itu doang yang ngebedain. Acara malem, semua nonton–kalo enggak diomelin orang tua. Ehem.
Hari ini, pengalaman itu menghilang. Kita hidup dalam era yang disebut para peneliti sebagai kematian monoculture moment; saat satu karya budaya bisa jadi pengalaman kolektif lintas kelompok. “No longer one audience, but millions of micro-audiences,” tulis Shani Orgad (profesor di bidang Media and Communications di London School of Economics, LSE). Kita semua terhubung, tapi masing-masing lewat jalur sendiri. Satu orang binge K-drama, satu lagi main TikTok, satu lagi nonton film festival. Algoritma memastikan lo tahu apa yang lo suka dan hanya itu.
Dalam karya-karyanya, Orgad membahas bagaimana media kontemporer, terutama media digital, telah mengubah kita dari publik massa yang kolektif menjadi kumpulan ‘audiens tersegmentasi’. Akibatnya, kamu bisa habis satu season dalam dua hari tanpa bisa ngobrolin apa-apa ke siapa-siapa. Karena enggak ada yang nonton itu. Atau belum. Atau udah, tapi udah lupa. Kamu nonton sendiri, mikir sendiri, selesai sendiri.
Sedih amat gitu, ya…. 😣
Monoculture mati, Obrolan Mati, Feed Menang
(Saya nyari tahu tentang Orgad dan monoculture moment ini dengan bantuan ChatGPT dan hasilnya … lagi-lagi, ngebikin saya ngebaca ini-itu sambil ngopi di depan PC, pikiran pun makin penuh. Jadi, perkara Orgad ini saya simpan dan kapan-kapan saya pikirin lagi. Hadeh.)
Kadang memang masih ada konten yang ‘menyatukan’ kita sejenak; anak-anak aura farming dari Pacu Lajur, kasus pembunuhan dengan bukti CCTV yang mengerikan dan entah mengapa tersebar padahal itu barang bukti, editan absurd yang tiba-tiba muncul di mana-mana. Tapi itu bukan monoculture, itu ledakan sesaat atau yang lebih kita kenali dengan istilah; viral. Dalam 24 jam, semua orang lihat, semua orang bereaksi, tapi enggak ada yang menetap. Kamu ikut nonton bukan karena mau merasakan, tapi karena takut ketinggalan.
Itu yang disebut sebagai virtual collective consciousness; kesadaran bersama yang muncul di dunia maya, lalu hilang seperti notifikasi. Kita nonton hal yang sama, tapi enggak benar-benar hadir di dalamnya.
Ray Oldenburg menyebut ini sebagai hilangnya third places; ruang netral tempat orang bisa nongkrong tanpa agenda (warung kopi, perpustakaan, ruang tamu, lapangan, atau angkringan di depan Indomaret). Sekarang, ruang-ruang itu diganti oleh layar.
Kita Bilang Kita Sibuk, Padahal Sebenarnya Enggak Punya Tempat Buat Hadir

Ini fotonya cerita mau menyesuaikan dengan tema tulisan ini gitu; Yaaa … ampyuuun, si Octa aloneee~
Dulu nonton bareng itu hal biasa. Sekarang, kita bahkan bingung harus ngajak siapa.
“Without them,” tulis Oldenburg, “communities decay, and the public realm ceases to exist.” Kita masih hidup dalam komunitas digital, tapi ruang publik untuk benar-benar berbagi makin runtuh.
Sekarang-karang ini, banyak yang berharap media sosial bisa menggantikan fungsi third place, jadi ruang netral tempat kita bisa ngobrol santai tanpa tekanan. Tapi kenyataannya, mayoritas platform justru lebih mirip etalase daripada warung kopi. Interaksinya sering performatif, penuh algoritma, dan terfragmentasi. Kita mungkin saling mention, saling lihat, saling reply, tapi jarang benar-benar duduk bareng, dalam arti yang sesungguhnya. Ray Oldenburg bilang, tanpa ruang-ruang informal itu, komunitas akan membusuk pelan-pelan.
Dan, kalau media sosial enggak bisa menggantikannya, kita perlu bertanya: di mana lagi kita bisa nongkrong hari ini, tanpa harus menjual versi terbaik dari diri kita sendiri?
Yang Kita Rindukan Bukan Filmnya, Series-nya, atau Lagunya, Tapi Rasa Bersamanya
Dalam filsafat eksistensial, banyak pemikir sudah lama mengantisipasi apa yang kita alami hari ini: keterhubungan tanpa kedekatan, informasi tanpa makna, dan aktivitas bersama yang kehilangan esensinya sebagai pertemuan.
Martin Buber dalam karyanya I and Thou (1923) menjelaskan bahwa hubungan manusia bisa dibagi menjadi dua: I–It dan I–Thou. Yang pertama adalah hubungan antara subjek dan objek; transaksional, efisien, tanpa kedalaman. Yang kedua adalah hubungan antar subjek, yang saling hadir, setara, dan utuh. Dunia digital, sayangnya, lebih mendorong kita ke dalam hubungan I–It, kita memperlakukan tontonan, bahkan manusia lain, sebagai objek konsumsi. Pertemuan berubah jadi aktivitas, bukan relasi.
(Ehem, iya … si Octa suka belajar filsafat. Pemisiii….)
Ketika kita nonton sendiri, bukan hanya teman yang hilang. Relasi itu sendiri yang runtuh. Kita tak lagi mengalami sesuatu bersama orang lain; kita hanya menyerap konten. Padahal, seperti kata Buber, “All real living is meeting.” Hidup yang benar-benar hidup adalah ketika ada perjumpaan. Dan dalam kultur digital, perjumpaan itu makin jarang terjadi.
Bentaaar … ini mengingatkan saya sama teori simulacra.
Filsuf Prancis Jean Baudrillard menyebut dunia modern sebagai simulacra; realitas semu yang meniru kehidupan tanpa benar-benar mengandungnya. Dalam bukunya Simulacra and Simulation (1981), doi bilang: “We live in a world where there is more and more information, and less and less meaning.” Kita bisa tahu semua plot twist dari serial yang belum kita tonton. Kita bisa ‘ikut ngobrol’ tentang film yang viral tanpa benar-benar mengalami filmnya. Nonton jadi ritual kosong. Yang bergerak hanya layar, bukan jiwa.
Kayaknya si Søren Kierkegaard juga ngeributin ini, deh. Bentar … saya googling. Saya enggak inget dia persisnya ngomong apaan. 😀
Dalam The Present Age (1846), doi menulis: “A reflective age is not an age of passion; it is an age of understanding and irony, and of infinite busy nothings.” Dunia kita sekarang penuh aktivitas, tapi miskin perjumpaan. Kita sibuk, tapi kesepian. Kita nonton terus, tapi enggak pernah betul-betul hadir.
(Bisa enggak, ya, gue jelasinnya dengan sederhana? Hmmm, mari dicoba.)
Si Om Kierkegaard menyebut zaman modern sebagai ‘usia reflektif’ yang dipenuhi ironi, jarak emosional, dan ‘infinite busy nothings’; kesibukan tanpa substansi. Dan rasanya, apa yang kita alami hari ini enggak jauh beda. Kita nonton banyak, tapi enggak pernah betul-betul hadir di dalam cerita. Kita tahu semua plot, semua twist, semua review, bahkan sebelum nonton. Kita aktif secara visual, tapi pasif secara eksistensial. Kita scroll sambil makan, nonton sambil kerja, ngikutin tren cuma supaya nyambung, bukan karena benar-benar tertarik. Seolah-olah, kita bergerak terus biar enggak perlu berhenti dan merasa. Nonton bukan lagi ruang untuk tersentuh, tapi pelarian cepat dari sunyi yang enggak kita akui. Kita enggak nonton buat hidup bareng; kita nonton biar bisa skip hidup itu sendiri.
Maka kalau kita nonton sendiri hari ini, lalu merasa kosong setelahnya, mungkin bukan karena filmnya jelek. Mungkin karena kita enggak tahu lagi cara nonton bareng. Kita enggak tahu siapa yang bisa kita ajak cerita. Kita enggak tahu di mana harus menyimpan emosi yang muncul.
Yang hilang dari hidup kita bukan tontonan, tapi kebersamaan. Kita enggak lagi menonton untuk mengingat. Kita menonton untuk melarikan diri. Kita tahu semua hal, tapi enggak tahu siapa yang bisa mendengarkan.
Dan, itu bukan salah kita. Itu dunia kita sekarang.
Mungkin jawabannya bukan soal kembali ke masa lalu. Kita enggak bisa maksa dunia berhenti bergerak, apalagi berharap semua orang duduk nonton televisi bareng lagi jam delapan malam. Tapi, di tengah dunia yang makin cepat, makin personal, dan makin sunyi, kita masih bisa nyari ruang yang benar-benar hidup. Ruang yang bukan sekadar timeline. Bukan sekadar tempat update atau scroll sampai lelah. Tapi ruang di mana kita bisa ngobrol tanpa tujuan, nonton tanpa harus menjual reaksi, hadir tanpa harus tampil.
Mungkin itu warung kopi. Mungkin itu ruang kecil di kampus. Mungkin itu chat grup yang enggak ada isinya kecuali stiker yang buriq dan mengada-ngada. Atau mungkin, kalau kita cukup nekat, kita bisa bangun ruang itu sendiri, di mana pun, asalkan ada manusia lain yang mau bareng. Karena pada akhirnya, yang kita cari dari sebuah tontonan bukan cuma cerita, tapi rasa kebersamaan.
Rasa yang enggak akan bisa berdiri sendirian.
Yah, gitulah….
Si Oma barusan dateng ke kamar dan nanyain tentang servis mesin jahit, jadi saya sudahi tulisan ini. Kepala isinya udah agak entengan, jadi abis ini saya mau lanjut ngerjain yang lain. Pembicaraan (dan tulisan) ini bisa dipanjang-panjangin ke mana-mana, tentu saja. Tapi, hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Yang penting, yang ganggu di otak, udah pindah ke sini. 😃
Manteman apa kabar?
* * *
