Saya pernah naik angkot, duduk di depan (di samping sopir), trus karena saya baca buku, sopirnya nanya, “Kuliah?”
Saya jawab, “Iya.”
Abis itu dia katanya punya pertanyaan dan mau ngetes apa saya bisa jawab.
Saya okein.
Pertanyaannya, “Kalo orang Islam, solat, tapi masih suka makan babi, gimana?”
Saya jawab, “Terserah Allah.”
Abangnya enggak terima jawaban itu karena menurut dia, saya harus bisa jawab.
Saya tanya balik, “Yang mau dijawab apa? Dia Islam dan solat? Atau dia solat dan makan babi? Atau dia makan babi?”
Abangnya bingung dan bilang saya enggak pinter blablablaaa….
Untungnya enggak lama saya udah turun.
Saya enggak ngeributin pekerjaannya sebagai sopir, tetapi emang pertanyaan itu perlu diperjelas untuk dijawab.
Di bis yang saya tumpangi berikutnya, saya mikirin si Abang itu karena kejadian kayak gini agak-agak jarang terjadi, ya. Saya biasanya ngambil tempat duduk di depan biar enggak diganggu, eh … ini malah abangnya yang ngajak ngobrol. Hadeh.
Saya paham si Abang Sopir itu enggak nyari jawaban, dia nyari:
- Validasi bahwa dia lebih paham agama,
- Kepuasan menilai siapa ‘pintar’ dan siapa ‘sesat’,
- Mau ngetes reaksi emosional saya, jadinya dia bukan mau percakapan intelektual.
Makanya waktu saya jawab, “Terserah Allah,” itu sebenarnya jawaban paling logis dan paling bisa saya kasih, karena:
- Konteksnya absurd,
- Premisnya amburadul,
- Saya bukan Tuhan.
Namun si abang enggak terima karena ekspektasinya: saya harus main di logika dia. Kalo saya enggak mau, saya minta definisi, maka, dia yang kalah debat sebelum debatnya mulai–saya enggak yakin dia paham ini.

Photo by Mathew Schwartz on Unsplash
Dunia Sudah Rusak, Tetapi Otakmu Masih Bisa Waras
Coba jawab cepat; kalo ada orang mencuri karena terpaksa, apakah dia jahat?
Kamu merasa ini pertanyaan gampang? Atau justru bikin mikir dua kali?
Menariknya, ini bukan soal benar atau salah. Ini soal cara kamu berpikir. Cara berpikir kamu itu akan menentukan:
- Bagaimana kamu mengambil keputusan,
- Bagaimana kamu menilai manusia,
- Dan, pada akhirnya, bagaimana kamu menjalani hidup.
Dalam Al-Qur’an, Allah berulang kali bertanya:
“Afala ta‘qilun?”
Tidakkah kamu berpikir?
Berpikir bukan cuma tugas kognitif. Itu perintah Tuhan. Tuhan, tuh, merintahin, “Otaknya dipakeee!”
Kita bahas dulu apa itu signal vs. noise sebelum bahas lagi pertanyaan di atas itu.
Signal vs Noise: Cara Bedah Pertanyaan Ambigu
Dalam dunia informasi (dan juga kehidupan), otakmu harus selalu memilah:
- Signal = hal-hal yang relevan dan penting untuk pengambilan keputusan.
- Noise = distraksi, manipulasi bahasa, asumsi, dan framing yang bikin kamu bias.
Contoh:
- Headline clickbait yang pakai emosi.
- Pertanyaan jebakan seperti; Apakah kamu membenci orang yang berbeda agama?
- Narasi politik yang sengaja bikin kamu marah duluan, mikir belakangan.
Kalo kamu tidak bisa menyaring signal dari noise, kamu akan hidup sebagai responden, bukan pemikir.
Contoh sederhanya; ketika publik disuruh marah karena seseorang mencuri, tetapi pernah dibahas kenapa sistem bikin dia kelaparan. Ketika influencer viral karena ‘menolong orang’, enggak ada yang bertanya; siapa yang menciptakan kondisi butuh ditolong itu?
Kamu diminta simpati, tetapi tidak diberi izin untuk berpikir. Kamu diajak emosi, tetapi dijauhkan dari akal sehat. Emosi emang bisa datang duluan, misalnya kayak yang saya tulis di post ini tentang pengalaman saya memahami patung laba-laba Maman, tetapi kemudian, saya mikir. Mikirnya emang ditunda tetapi enggak ditiadakan.
Belajar dari Pertanyaan Ambigu
Kita balik lagi ke pertanyaan di atas itu. Coba kita bedah. Pertanyaannya; kalau ada orang mencuri karena terpaksa, kamu anggap dia orang jahat?
Sebelum buru-buru jawab, mending kita urai dulu elemen-elemennya:
- Aksinya; mencuri,
- Kondisinya; terpaksa,
- Pertanyaannya ngajak kita kasih label; orang jahat apa bukan?
Lalu kita lihat, ada kata-kata yang patut diwaspadai. Misalnya, ‘terpaksa’. Terpaksa yang kayak gimana. Enggak punya duit buat makan, atau enggak bisa nahan beli iPhone? Lalu, ‘orang jahat’. Ini label besar. Kayak ngasih label seluruh hidup orang itu cuma dari satu tindakan.
Jadi wajar kalau kita pertanyakan dulu asumsi-asumsinya:
- Emang satu tindakan bisa langsung nentuin karakter seseorang?
- Emang ‘terpaksa’ itu berarti enggak ada opsi lain sama sekali?
Dari situ, kita bisa ambil posisi yang lebih adil. Mungkin kita sepakat; mencuri itu salah. Tetapi apakah otomatis pelakunya jahat? Belum tentu.
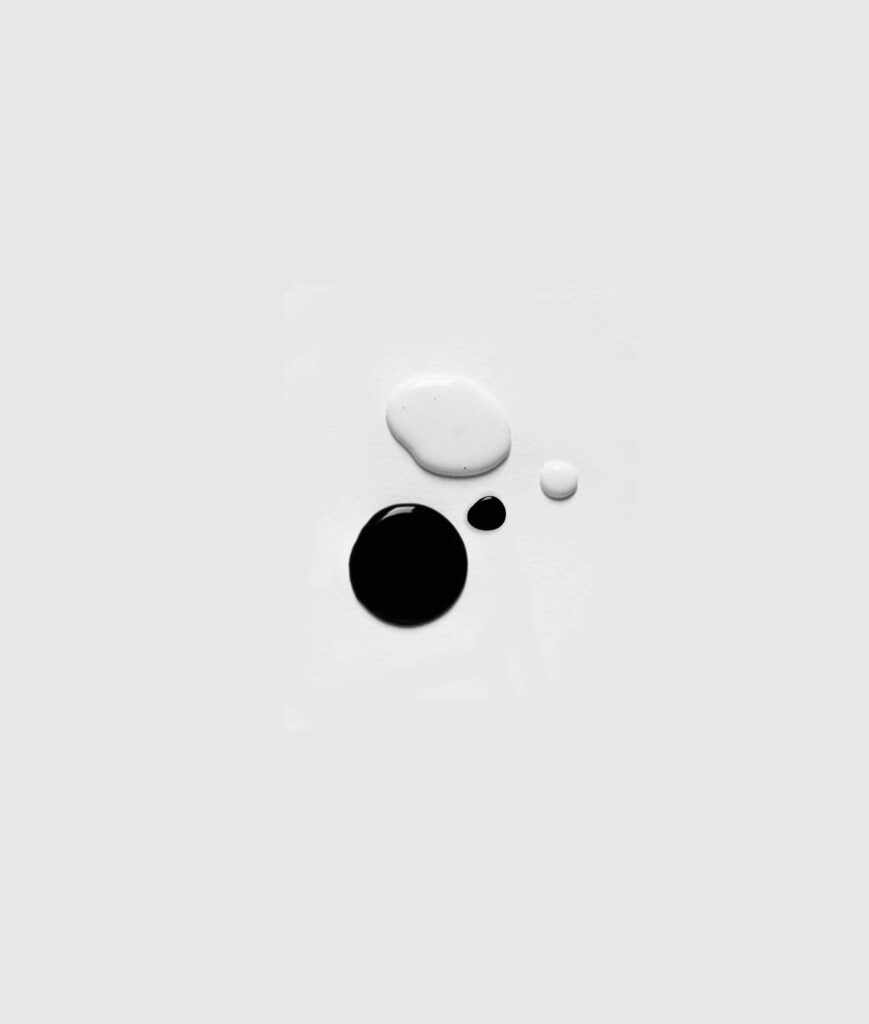
Photo by Allec Gomes on Unsplash
Apa yang Kamu Latih Saat Bedah Pertanyaan Ambigu?
1. Identifikasi Struktur Soal (Parsing)
Tentukan elemen kunci dalam pertanyaannya? Kayak kita lakuin tadi; mencuri, terpaksa, orang jahat ~> itu variabel logika utama.
Skill yang dilatih:
- Pemecahan masalah,
- Fokus terhadap premis, bukan asumsi.
2. Deteksi Noise dan Framing
Kata ‘terpaksa’ = bisa noise kalau enggak diklarifikasi.
Kata ‘orang jahat’ = loaded phrase ~> perlu dibongkar.
Skill yang dilatih:
- Sensitivitas terhadap framing,
- Ngeh saat bahasa bikin lo terjebak,
- Deteksi red herring, logical fallacy, dan manipulasi bahasa.
3. Prioritaskan Nilai Relevan
Kamu belajar enggak semua kata punya bobot sama.
Contoh:
- ‘Terpaksa’ bisa bobot tinggi (kalau diancam senjata),
- Bisa juga bobot rendah (kalau cuma males bayar).
Skill yang dilatih:
- Kalibrasi; menimbang nilai argumen,
- Menentukan konteks penting sebelum tarik kesimpulan.
4. Skeptisisme Fungsional
Enggak langsung percaya konteks yang dikasih.
Kamu latih diri buat nanya:
- Siapa yang bikin pertanyaan ini?
- Apa agenda atau asumsi yang diselipkan?
- Apakah opsinya sengaja dibatasi?
Skill yang dilatih:
- Skeptisisme aktif (bukan sinis, tapi awas),
- Navigasi ruang abu-abu.
5. Pengambilan Keputusan Reflektif
Setelah kamu pisah signal dari noise, baru lo putuskan; sikap saya apa?
Skill yang dilatih:
- Meta-cognition (lo sadar gimana cara lo berpikir),
- Pengambilan keputusan dengan struktur argumen, bukan reaksi impulsif.
Ngulik pertanyaan ambigu = latihan gym buat otak lo biar bisa deteksi bullshit, filter prioritas, dan ngambil sikap yang enggak asal tembak.
Sama kayak badan yang bisa dilatih buat squat atau push-up, otak bisa dilatih buat:
- Bedain mana substansi, mana dramatisasi,
- Mana fakta dan framing,
- Mana informasi dan distraksi.
Manfaatnya ketika kamu berlatih mikir kayak gini dan ngajarin ke anak-anak kamu … nganuuu … hidupmu sehari-hari adalah usaha untuk meyakinkan anak-anak kamu kalo hal-hal yang kamu suruh itu masuk akal. T_____________________T
Kenapa Ini Penting di Dunia yang Carut Marut?
Hari ini, kamu diserbu:
- Algoritma yang memancing amarah,
- Influencer yang menjual kebodohan kolektif,
- Narasi politik yang memecah belah lewat manipulasi moral.
Kalau kamu tidak melatih otak untuk berpikir jernih dan adil, maka kamu bukan hanya jadi korban, tetapi juga bisa jadi pelaku ketidakadilan yang kamu kira benar.
Kalau kamu ingin bertahan dengan kepala jernih di tengah dunia penuh framing, kamu tidak perlu jadi jenius. Kamu hanya perlu satu hal; kemauan untuk berpikir.
Karena dalam hidup, bukan hanya jawaban yang penting, tetapi bagaimana kamu menjawab dan bagaimana cara kamu berpikir.
Atau, kalo disingkat, tulisan sepanjang ini pesannya cuma satu; makanya mikir!
Afala ta‘qilun?
***
Tulisan ini saya buat karena tadi pagi, saya mencoba menjawab pertanyaan ini di Threads. 🥰
